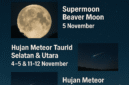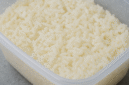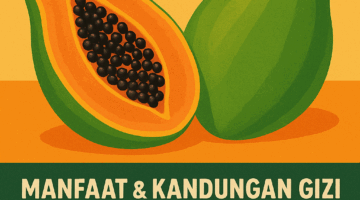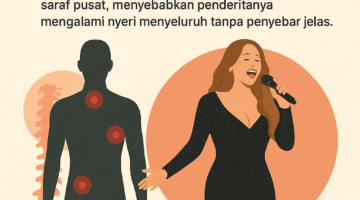Polemik royalti lagu di Indonesia seolah tak pernah benar-benar reda. Di satu sisi, pencipta lagu berhak mendapatkan kompensasi atas karya mereka—sebuah bentuk penghargaan yang diatur undang-undang dan diakui secara moral. Di sisi lain, mekanisme perhitungan, penarikan, dan penyaluran dana sering kali membingungkan, bahkan bagi pelaku industri itu sendiri.
Secara sederhana, royalti dihitung berdasarkan jumlah pemutaran atau penggunaan lagu di ruang publik maupun media digital. Di platform streaming, rumusnya umumnya melibatkan pro-rata share: total pendapatan dari langganan dan iklan dibagi jumlah total pemutaran, lalu dikalikan jumlah stream lagu tertentu. Di ranah offline, seperti kafe, hotel, atau stasiun TV, perhitungannya memakai tarif lisensi tahunan atau bulanan yang ditentukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lalu dibagi sesuai data penggunaan lagu.
Dana yang terkumpul dari pengguna (baik individu maupun institusi) akan masuk ke LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terkait. Di sinilah muncul lapisan kerumitan: data pemutaran sering kali tak lengkap, metode pelaporan bervariasi, dan distribusi dana kerap memunculkan pertanyaan. Idealnya, setiap rupiah yang dibayarkan oleh pengguna musik akan ditelusuri kembali ke pencipta lagu yang karyanya digunakan. Namun, realitanya, masih ada gap antara transparansi yang diharapkan dan yang terjadi.
Polemik muncul bukan hanya karena nominal yang diterima pencipta dianggap kecil, tetapi juga karena kurangnya keterbukaan dalam proses. Apakah dana benar-benar dibagikan sesuai proporsi pemakaian? Bagaimana nasib royalti dari karya yang pemutarnya sulit dilacak? Dan mengapa sistem ini seakan “tertutup” bagi pencipta untuk memverifikasi?
Idealnya, ada sistem yang dibangun secara transparan dan wajib digunakan. Bayangkan satu aplikasi resmi yang menjadi standar nasional untuk pemutar musik di kafe, restoran, atau tempat umum lain. Aplikasi ini terhubung langsung ke server pusat yang secara real time mengumpulkan data lagu apa saja yang diputar dan berapa kali setiap lagu diputar. Data tersebut otomatis menjadi dasar perhitungan royalti, menghilangkan celah manipulasi atau laporan manual yang rawan salah. Lebih penting lagi, aplikasi ini seharusnya dapat diakses oleh para pencipta lagu, sehingga mereka dapat memantau secara langsung performa karyanya dan memastikan perhitungan royalti yang adil.
Saya berpendapat, kunci penyelesaian bukan sekadar menaikkan tarif royalti atau memaksa pengguna musik membayar lebih, melainkan membangun sistem yang transparan, terukur, dan dapat diaudit. Pencipta lagu berhak tahu berapa kali lagunya diputar dan dari mana uangnya berasal. Di era digital, teknologi pelacakan sudah ada—tinggal kemauan dan integritas lembaga pengelola untuk menggunakannya secara optimal.
Tanpa transparansi, royalti hanyalah angka di atas kertas; tanpa keadilan, musik hanyalah hiburan yang menguntungkan segelintir pihak. Jika kita mengaku menghargai karya seni, maka menghargai hak ekonomi penciptanya adalah kewajiban, bukan pilihan.