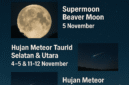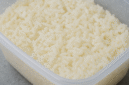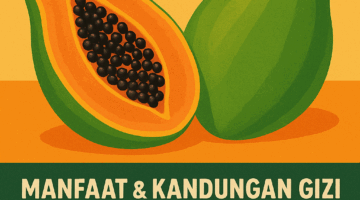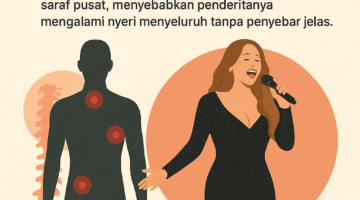Elang jawa, yang menjadi maskot satwa langka Indonesia. Dalam situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan, elang jawa termasuk spesies yang terancam punah.
Dalam daftar merah Badan Konservasi Dunia (IUCN), elang jawa masuk dalam status terancam punah (endangered). Pada tahun 2005, populasi elang jawa sebanyak 425 pasang dan pada tahun 2010 menjadi 325 pasang. Populasi tersebut kian menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 188 pasang.
Elang yang bertubuh sedang sampai besar, langsing, dengan panjang tubuh antara 60–70 cm (dari ujung paruh hingga ujung ekor).
Kepala berwarna cokelat kemerahan (kadru), dengan jambul yang tinggi menonjol (2–4 bulu, panjang hingga 12 cm) dan tengkuk yang cokelat kekuningan (kadang tampak keemasan bila terkena sinar matahari). Jambul hitam dengan ujung putih; mahkota dan kumis berwarna hitam, sedangkan punggung dan sayap cokelat gelap. Kerongkongan keputihan dengan garis (sebetulnya garis-garis) hitam membujur di tengahnya. Ke bawah, ke arah dada, coret-coret hitam menyebar di atas warna kuning kecokelatan pucat, yang pada akhirnya di sebelah bawah lagi berubah menjadi pola garis (coret-coret) rapat melintang merah sawo matang sampai kecokelatan di atas warna pucat keputihan bulu-bulu perut dan kaki. Bulu pada kaki menutup tungkai hingga dekat ke pangkal jari. Ekor kecokelatan dengan empat garis gelap dan lebar melintang yang tampak jelas di sisi bawah, ujung ekor bergaris putih tipis. Betina berwarna serupa, sedikit lebih besar.
Iris mata kuning atau kecokelatan; paruh kehitaman; sera (daging di pangkal paruh) kekuningan; kaki (jari) kekuningan. Burung muda dengan kepala, leher, dan sisi bawah tubuh berwarna cokelat kayu manis terang, tanpa coretan atau garis-garis.
Ketika terbang, elang jawa serupa dengan elang brontok (Nisaetus cirrhatus) bentuk terang, namun cenderung tampak lebih kecokelatan, dengan perut terlihat lebih gelap, serta berukuran sedikit lebih kecil.
Bunyi nyaring tinggi, berulang-ulang, klii-iiw atau ii-iiiw, bervariasi antara satu hingga tiga suku kata. Atau bunyi bernada tinggi dan cepat kli-kli-kli-kli-kli. Sedikit banyak, suaranya ini mirip dengan suara elang brontok meski perbedaannya cukup jelas dalam nadanya.

Sesungguhnya keberadaan elang jawa telah diketahui sejak sedini tahun 1820, tatkala van Hasselt dan Kuhl mengoleksi dua spesimen burung ini dari kawasan Gunung Salak untuk Museum Leiden, Negeri Belanda. Akan tetapi pada masa itu hingga akhir abad-19, spesimen-spesimen burung ini masih dianggap sebagai jenis elang brontok.
Baru pada tahun 1908, atas dasar spesimen koleksi yang dibuat oleh Max Bartels dari Pasir Datar, Sukabumi pada tahun 1907, seorang pakar burung di Negeri Jerman, O. Finsch, mengenalinya sebagai takson yang baru. Ia mengiranya sebagai anak jenis dari Spizaetus kelaarti, sejenis elang yang ada di Sri Lanka. Sampai kemudian pada tahun 1924, Prof. Stresemann memberi nama takson baru tersebut dengan epitet spesifik bartelsi, untuk menghormati Max Bartels di atas, dan memasukkannya sebagai anak jenis elang gunung Spizaetus nipalensis.
Demikianlah, burung ini kemudian dikenal dunia dengan nama ilmiah Spizaetus nipalensis bartelsi, hingga akhirnya pada tahun 1953 D. Amadon mengusulkan untuk menaikkan peringkatnya dan mendudukkannya ke dalam jenis yang tersendiri, Spizaetus bartelsi.
Burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia identik dengan Elang Jawa, namun sebenarnya burung Garuda adalah mahluk mitologi.
Nama Garuda sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta. Ia merupakan kendaraan atau wahana Dewa Wisnu, dewa pemelihara alam semesta, dalam agama Hindu.
Dikutip dari laman Museum Nasional, Garuda seringkali dilukiskan memiliki kepala, sayap, ekor dan moncong burung elang, dengan tubuh, tangan, dan kaki bak manusia.